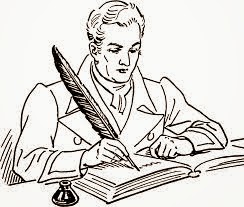|
Resensi Saya dimuat di KORAN JAKARTA,
Februari 2013
|
Data Buku:
Judul Buku : FALSAFAH
JAWA SOEHARTO & JOKOWI, Menjadi Pemimpin
Kharismatis ala Soeharto dan Jokowi
Penerbit
: Araska
Penulis
: Ki Nardjoko Soeseno
Terbit
: I, Januari 2013
Tebal
: 154
ISBN
: 978-602-7733-82-4
Oleh :Danang Probotanoyo
Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman paling banyak di
dunia. Contohnya dalam jumlah suku
bangsa. Menurut catatan BPS ( 2010), Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Dari
sebanyak itu, Suku Jawa merupakan suku
yang paling menonjol. Salah satu penyebabnya terkait jumlah populasi etnik Jawa
yang mencapai 40% dari total populasi rakyat Indonesia. Implikasinya, nyaris di
segala sendi kehidupan negeri ini etnis Jawa tampak dominan, tak terkecuali di ranah politik
kekuasaan. Dari enam presiden yang pernah dimiliki negeri ini, hanya Habibie
yang beretnik non-Jawa. Akibatnya mau tak mau, suka tidak suka, budaya dan
falsafah hidup orang Jawa mewarnai idiomatical
politik-kekuasaan di Indonesia.
Berbicara hal etnik dan budaya Jawa, tak bisa lepas dari dua pusat kebudayaan Jawa,
yakni Yogyakarta dan Surakarta (Solo). Beberapa pemimpin Indonesia modern yang
berasal dari dua daerah tersebut memiliki gaya kepemimpinan yang kental dengan falsafah
dan budaya Jawa. Lepas dari kelebihan dan kekurangannya, sosok Soeharto dan
Jokowi adalah contoh pemimpin yang ‘Njawani’ (kental nilai-nilai Jawa-nya).


Soeharto yang pernah memimpin negeri ini hingga 32 tahun adalah figur
pemimpin yang gigih meletakkan falsafah dan nilai-nilai budaya Jawa dalam corak
dan strategi kepemimpinannya. Sejarah masa kecil hingga remajanya yang sarat
dengan kepahitan hidup, telah menempa
Soeharto sebagai sosok yang gemar ‘laku’ olah batin dan olah rasa. Segala
perilaku, ucapan hingga bahasa tubuhnya merefleksikan nilai-nilai dan falsafah
orang Jawa. Terlepas dari penilaian bahwa Soeharto otoriter, namun harus diakui
semasa berkuasa ia disegani kawan maupun lawan. Tak ada yang berani membantah
ucapan dan perintahnya. Semua pembantu dekatnya termasuk para menteri merasa perlu
mendapatkan ‘restu’ dahulu untuk sekedar bicara ke publik. Kalimat,
“Menurut petunjuk bapak presiden,” ala Harmoko saat menjabat sebagai menteri
penerangan, merefleksikan pentingnya restu Soeharto dalam segala hal. Ada lagi Moerdiono,
selaku menteri sekretaris negara, bergaya bicara yang kelewat lambat, takut salah
dalam menerjemahkan maksud Soeharto.
Soeharto orangnya cenderung pendiam, tenang dan penuh misteri. Tak
pernah meledak-ledak. Senyum pun hanya dalam kadar minimalis. “The smiling
general” label orang terhadap Soeharto
yang memiliki senyum khas. Diamnya Soeharto bukanlah diamnya orang kebanyakan atau
diamnya orang yang tak pandai bicara. Diamnya Soeharto sebagai perwujudun ‘Laku Tapa Meneng’ yang ia jalani sejak
tahun 1936 dibawah bimbingan Kyai Daryatmo. Falsafah: Ojo Lali, Ojo Kagetan dan Ojo Dumeh merupakan fase pengalaman batin
yang harus dilalui Soeharto sebelum mencapai level Meneng atau ‘diam’ (hal 31). Dengan Meneng, manusia diharapkan bisa mengalahkan dirinya sendiri menuju
kesempurnaan hidup. Hasilnya, Soeharto berhasil menguasai jutaan manusia lain
serta menguasai sistem masyarakat dalam tempo relatif lama. Soeharto pun termasuk
orang Jawa yang setia pada ajaran ‘pituduh’
atau bimbingan dan sebisa mungkin menghindari ‘wewaler’ atau larangan dalam
budaya Jawa. Satu contohnya, usaha Soeharto dalam mengamalkan petuah ‘mikul dhuwur mendhem jero’, yang artinya sebisa mungkin mengangkat
kebaikan orang dan menyimpan kesalahan orang tersebut. Meski memandang
pendahulunya, Presiden Soekarno, memiliki kesalahan, namun Soeharto tidak mau
mengadilinya (hal 36).
 Indonesia masa kini pun memiliki Jokowi sebagai representasi pemimpin
yang sarat dengan falsafah budaya Jawa dalam memimpin. Profil Jokowi yang
kelewat sederhana dibanding jabatannya
serta gaya kepemimpinannya yang merakyat refleksi nilai-nilai budaya Jawa: ‘ojo dumeh’ (jangan mentang-mentang). Memenangkan
dua kali pemilihan Walikota Solo – periode II dengan angka di atas 90% -- yang
berlanjut dengan terpilihnya Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi bukti
kecintaan rakyat pada pemimpin yang bersahaja dan merakyat. Meski bermodal kapital relatif kecil dibanding lawannya, namun dengan
pendekatan langsung ke rakyat kecil dan marginal, Jokowi menang dalam pilgub DKI.
Falsafah yang dipegangnya adalah ‘Jaya
Tanpa Banda’ (menang dengan harta yang tak berlebih). Kemenangan yang
didapat pun tak membuatnya jumawa. Ia amalkan petuah bijak Jawa ‘Menang Tanpa Ngasorake’, mencapai kemenangan
tanpa mempermalukan pihak yang kalah (hal 55). Usai pemilukada langsung
menyambangi Fauzi Bowo, bahkan meminta maaf karena telah ‘menyusahkannya’.
Sikapnya pun sangat terpuji ketika secara spontanitas mencium tangan Bibit
Waluyo, Gubernur Jawa Tengah, mantan atasannya yang pernah menghina dengan
mengatakan ia sebagai ‘orang bodoh’, padahal jabatannya sekarang setara dengan
Bibit bahkan lebih prestisius.
Indonesia masa kini pun memiliki Jokowi sebagai representasi pemimpin
yang sarat dengan falsafah budaya Jawa dalam memimpin. Profil Jokowi yang
kelewat sederhana dibanding jabatannya
serta gaya kepemimpinannya yang merakyat refleksi nilai-nilai budaya Jawa: ‘ojo dumeh’ (jangan mentang-mentang). Memenangkan
dua kali pemilihan Walikota Solo – periode II dengan angka di atas 90% -- yang
berlanjut dengan terpilihnya Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi bukti
kecintaan rakyat pada pemimpin yang bersahaja dan merakyat. Meski bermodal kapital relatif kecil dibanding lawannya, namun dengan
pendekatan langsung ke rakyat kecil dan marginal, Jokowi menang dalam pilgub DKI.
Falsafah yang dipegangnya adalah ‘Jaya
Tanpa Banda’ (menang dengan harta yang tak berlebih). Kemenangan yang
didapat pun tak membuatnya jumawa. Ia amalkan petuah bijak Jawa ‘Menang Tanpa Ngasorake’, mencapai kemenangan
tanpa mempermalukan pihak yang kalah (hal 55). Usai pemilukada langsung
menyambangi Fauzi Bowo, bahkan meminta maaf karena telah ‘menyusahkannya’.
Sikapnya pun sangat terpuji ketika secara spontanitas mencium tangan Bibit
Waluyo, Gubernur Jawa Tengah, mantan atasannya yang pernah menghina dengan
mengatakan ia sebagai ‘orang bodoh’, padahal jabatannya sekarang setara dengan
Bibit bahkan lebih prestisius.
Tanpa menafikan keluhuran nilai-nilai budaya etnik lainnya, buku ini
sekedar ingin memperkenalkan falsafah dan nilai budaya Jawa dalam praktek
kepemimpinan ala Soeharto dan Jokowi.