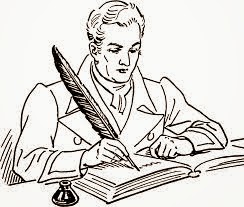Oleh: Danang Probotanoyo
 |
| Cerpen Saya Termuat di Harian Rakyat Sumbar Medio: Agustus 2016 |
“Paling tidak kamu masih punya waktu untuk bertobat, jangan pernah mengharapkan mati menghampiri lebih dini,” ujar Sholeh teman satu selku.
“Bertobat?! Huh, Tuhan mungkin bisa memaafkanku, tapi, aku sendiri tak akan pernah bisa memaafkan diriku lagi,” jawabku mantab.
“Ini sungguh tak adil! dipenjara selama tujuh tahun teramat ringan bagiku. Betapa ini sangat menyiksaku,” ujarku.
Setahun yang lalu aku hidup normal bersama keluargaku. Namaku Yanto, aku anak kedua dari dua bersaudara. Marwan kakakku tipe sulung yang bisa dijadikan panutan. Dia rajin sembahyang. Sekolahnyapun sarat prestasi yang terpuji. Bapakku seorang pegawai biasa di satu kantor ekspor-impor. Ibuku seperti kebanyakan ibu-ibu jaman dahulu, yang menempatkan tugas sebagai ibu rumah tangga sebagai karir perempuan yang mulia. Walau segala kebutuhan dalam batasan tertentu sudah terpenuhi, aku tetaplah tipikal remaja yang selalu punya keinginan. Hidup di Jakarta penuh godaan dan tantangan. Tak terlalu hedonis memang, tapi setidaknya aku selalu mempunyai keinginan yang datangnya mendadak dan terkadang tanpa ukuran. Jika sudah begitu aku tak mau meminta pada orang tuaku. Karena aku tahu, mereka tak sanggup memberi lebih dari takaran yang semestinya. Aku juga malu kepada Marwan yang tak pernah menyusahkan orang tua dengan keinginan-keinginan yang tak perlu. Aku tak perduli dengan sikap Marwan yang serba menerima apa adanya. Aku adalah aku! Marwan adalah Marwan! Aku bukan anak penurut. Tapi, setidaknya dihadapan keluargaku aku selalu tampak terang dengan menyembunyikan sisi gelapku. Aku punya keinginan tapi orang tuaku hanya memberi sebatas kebutuhan. Aku punya teman-teman pergaulan yang hobinya nongkrong di warung internet untuk main game online tanpa batas. Kami pun main bilyar sebagai selingan. Terkadang kami juga pergi ke club untuk hangout seperti anak metropolitan lainnya. Sesekali kami patungan untuk menjemput impian berkawan dengan daun dan serbuk jahanam. Kami anak jalanan di metropolitan. Bersama Bagus karibku dalam kawanan, aku sering berpetualang. Bukan petualangan yang biasa. Namun petualangan penuh bahaya yang bisa mengancam jiwa secara tak terhormat. Semuanya demi keinginan yang melampaui kemampuan. Seperti siang itu.
“Di sebelah sana, Gus! Megapro hijau metalik itu kayaknya ok,” ujarku dari boncengan.
“Gile cing! masih mulus, sasaran empuk, nih,” Bagus menimpali.
Kami pun memarkir motor disebelah motor yang telah kami targetkan. Bukan, kami bukan mau nyolong Megapro hijau itu. Kami belumlah seprofesional itu. Kami tetaplah sekedar kawanan yang memiliki keinginan. Tak lebih dari itu. Setelah berpura-pura ke toilet sebentar, kami pun balik ke motor.
“Ada logo SNI nya, Gus!” ujarku, setelah meraih helm dari Megapro hijau disebelah.
“Itu yang penting, Tok! Sama-sama beresiko kita mesti pilih-pilih, kan hasilnya lumayan,” sergah Bagus.
Sejurus kemudian, kami pun meninggalkan tempat parkir tersebut. Walau maling helm kelas teri dan masih amatiran, dalam arti nyolong hanya untuk senang kecil-kecilan dan bukan untuk nafkah, tapi kami tetap melakukannya serapi dan seprofessional mungkin. Terbukti, walau hampir setiap hari kami melakukannya, namun satu kali pun belum pernah apes. Hanya maling tolol yang bisa tertangkap basah, itulah motto yang tak pernah kami deklarasikan. Dari perilaku menyimpang tersebut paling tidak kami memperoleh uang tambahan antara seratus hingga dua ratus ribu rupiah sekali beraksi. Kalau sudah begitu, kami merasa cukup pede untuk pergi main game online, ke tempat bilyad atau sekedar kongkow-kongkow sambil nyimeng dan sedikit minum-minum. Ingat, kami punya keinginan bukan sekedar kebutuhan. Kami masih muda jadi tak pernah mikirin dosa. Atau memang kami tak tahu atau tak mau tahu, apa itu dosa?
Di dalam sel penjara, menurutku, hanya Sholeh satu-satunya tipe manusia yang terpeleset dan masuk perangkap penjara yang pengap tanpa kesadaran sendiri. Walau hingga saat ini aku tak pernah mengindahkan ocehannya yang terkadang seperti kutbah kyai. Lain kali bak Andri Wongso dalam sesi motivasi. Namun, aku nyaman berteman dengan Sholeh di penjara. Namanya saja Sholeh! bukan Premana (yang bisa diplesetkan Preman) apalagi Mangliki (plesetan Maling).
“Jadi, kamu dihukum tujuh tahun penjara hanya gara-gara nyolong helm!” seru Sholeh penuh kegeraman sekaligus keheranan.
“Sungguh tak ada keadilan di negeri ini, Ayin yang terbukti menyuap seorang jaksa saja cuma kena empat tahun. Bahkan dari berita di TV hukuman si Ayin malah dikurangi oleh para hakim agung. Belum lagi ada dua jaksa cewek yang nilep 300 butir ekstasi, satunya cuma dihukum setahun, satunya lagi malah bebas,” protes si Sholeh dengan berapi-api.
Tak seperti kebanyakan napi, Sholeh memang paling doyan nonton berita TV, di depan pos jaga sipir tiap blok.
“Bukan karena nyolong helm, Leh, aku dipenjara. Aku membunuh Marwan kakakku dengan sebatang kayu dalam satu perkelahian!” jawabku getir.
Dua tanganku menggenggam erat jeruji sel yang dinginnya seperti es. Sambil menerawang liar ke arah luar. Lidahku terasa kelu, namun kuputuskan untuk memaksanya berkata-kata dan bercerita kepada Sholeh.
Jam enam sore, lebih dari setahun yang lalu, ketika kawanan kami sedang asyik berkongkow-kongkow, tiba-tiba datang SMS dari Marwan, “Cepat ke UGD RS Cipto! Bapak kecelakaan, aku dan ibu sudah disini.” Empat puluh lima menit sampailah aku di UGD RS Cipto.
“Suster, disebelah mana Pak Sutarjo?” aku menyebut nama bapakku.
“Maaf, lima menit yang lalu Pak Sutarjo baru saja dipindah….”
“Pindah ke bangsal perawatan apa, Sus?!” aku memburu.
“Maaf, mas, kami menyesal, Pak Sutarjo tidak tertolong jiwanya, baru saja beliau dibawa ke kamar jenazah.”
Jeder!! bak sambaran petir mengena dengan telak dan tepat di tengah dadaku, mendengar kabar demikian.
Di kamar jenazah RS Cipto, kulihat ibuku meraung-raung seperti tak ikhlas ditinggal bapak yang secara tiba-tiba itu. Maklum, bapak-ibuku adalah gambaran ideal sepasang laki-perempuan yang saling mengasihi yang dipersatukan dalam ikatan bahtera rumah tangga. Bahkan, seperti yang pernah diceritakannya kapadaku dan Marwan, mereka sudah berpacaran semenjak kelas satu SMA! Kulihat Marwan sesenggukan sambil mencoba tabah dan menenangkan Ibu. Di kamar jenazah sudah banyak teman-teman bapak. Sebagian mencoba menenangkan dan menguatkan kami, sebagian lagi dan dua orang polisi tengah merubung Om Doni kawan kerja bapak. Kulihat Om Doni sebelah tangannya digendong dengan perban. Beberapa bagian mukanya lebam kemerah-merahan diberi Bethadine. Akhirnya aku tahu bahwa Om Doni merupakan kawan bapak dalam kecelakaan tersebut.
Sholeh mencoba memecah keheningan yang sesaat di dalam sel kami, “Kalau boleh tahu, apakah kalian berkelahi karena masalah warisan bapakmu, atau apa? Sehingga satu diantara kalian sampai terbunuh,” Selidik Sholeh dengan hati-hati.
Akupun tiba-tiba sesenggukan tak kuasa menahan tangis yang terus kucoba membendungnya sejak tadi. Dengan bersandar di tembok sel, kedua tanganku mencengkeram erat rambutku sendiri. Sambil sesekali berdecak khas milik orang yang sedang menyesal teramat dalam.
Ya, Aku membunuh Marwan kakakku satu-satunya tepat di malam kematian Bapak. Semuanya benar-benar terjadi tanpa rencana. Semua itu memang sudah menjadi kehendak Ilahi. Dari penuturan Om Doni, dihadapan kawan-kawan bapak lainnya, aku baru tahu bahwa sore itu, seusai jam kerja, bapak diberi boncengan motor oleh Om Doni. Kebetulan pada sore itu Om Doni tidak menjemput istrinya di kantor sebelah. Sang istri minta ijin kantornya untuk pulang lebih awal karena anaknya sakit panas di rumah. Bapakpun senang, karena trayek angkutan yang biasa ditumpangi, hari itu sedang melakukan mogok masal karena sesuatu alasan. Di tengah perjalanan mereka berdua mampir di satu super market membeli obat dan buah untuk anak Om Doni. Dalam perjalanan pulang, di satu jalan, Om Doni dikejutkan oleh seorang pengamen muda yang tiba-tiba muncul dari balik pohon peneduh di pinggir jalan. Pengamen tersebut langsung nyelonong mengejar bis kota diseberang jalan. Fatalnya, dia memotong jalan yang dilalui Om Doni tanpa menoleh sedikitpun. Karena Om Doni cukup kencang memacu motornya, sontak untuk menghindari pengamen tersebut, Om Doni banting stang ke kiri dan menghantam bibir trotoar tanpa ampun. Mereka berdua terpelanting dalam gerak akrobatik yang dramatis ke jalanan. Pengamen itupun hanya berlalu tanpa pernah merasa bersalah.
“Trus, apa yang menyebabkan kamu dan Marwan berkelahi dengan sengit di malam kematian bapakmu?” tanya Sholeh sembari memegang bahu belakangku.
Untuk pertanyaan Sholeh yang terakhir itu, pecahlah raunganku sejadi-jadinya. Beberapa napi dan sipir berdatangan ke arah sel kami.
“Berdasar cerita Om Doni yang mendetail, tahukah kau, Leh? Akulah yang telah membunuh bapakku sendiri!” ujarku dengan terisak dan sesak nafas. Karena tak bisa menerima kelakuanku yang telah menyebabkan bapak mati, malamnya Marwan menghajarku habis-habisan. Semula aku tak berusaha melawan karena rasa salahku. Namun, karena Marwan semakin kalap dan nekad mengambil pisau dapur untuk menghabisiku, dalam keadaan terdesak aku pun meraih sepotong kayu didekatku. Dan, dengan sekali hantaman yang sangat keras membuat Marwan terkapar dengan tengkorak yang pecah.”
“Bagaiman bisa kamu katakan bahwa bapakmu mati olehmu?” desis Sholeh terbata-bata.
“Akulah yang mengambil helm Om Doni! yang seharusnya dikenakan bapak, ketika mereka mampir di super market itu. Akulah yang menyebabkan kepala bapak pecah beradu dengan kerasnya aspal tanpa mengenakan helm yang kucuri itu!”
“Aku benar-benar manusia iblis! Yang telah membunuh bapak dan saudaraku satu-satunya di hari laknat itu! Aku pula yang menyebabkan ibuku menjadi gila, menyusuri setiap rel kereta, berakhir tatkala sebuah kereta ekspres menyambarnya, hingga meremukkan kepala!”
Danang Probotanoyo, Esais, Cerpenis, Yogyakarta, 2015