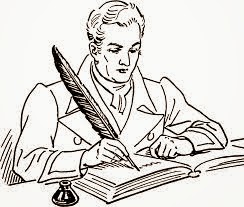|
Resensi Saya di Seputar Indonesia
(Koran Sindo), Desember 2012
|
Judul Buku : LUPA ENDONESA
Penulis
: Sujiwo Tejo
Penerbit
: Bentang (PT Bentang Pustaka)
Cetakan
: September 2012
Tebal
: xiii + 218
ISBN
: 978-602-8811-87-3
“Tulisannya memang ‘kurang
ajar’”, kata Dahlan Iskan dalam pengantar buku ini (viii). Bagi yang kenal atau
sekadar tahu saja, siapa dan bagaimana Sujiwo Tejo, tentu sepakat dengan Dahlan
Iskan. Julukan “Dalang Edan” atau “Dalang Mbeling” sudah
lama disematkan orang kepada Sujiwo Tejo. Dalang asal Jember lulusan ITB ini
pantas mendapatkannya, sebab dalam setiap pementasan wayang kulitnya,
Sujiwo jarang mengandalkan cerita pakem yang selama ini
dipegang teguh para dalang kesohor dan sepuh dari tanah Jawa. Sering cerita
dibuatnya sendiri, bersumber dari situasi dan kondisi sosial, politik dan
berbagai fenomena yang sedang hangat dibicarakan. Kalau, toh, memainkan cerita atau lakon wayang yang pakem, Sujiwo dengan
nakalnya membelokkan alur cerita secara liar ke berbagai arah. Dialog para
wayang kerap diisi humor satir bahkan
sarkastik yang bisa mengenai siapa saja, baik politisi, aparat hukum hingga ke penguasa
negeri. Kritis dan humoris, itulah dua
kata yang akan dilontarkan orang ketika
menyaksikan pertujukan wayang dan membaca tulisan-tulisan Sujiwo.
Kemampuannya mengurai dan mengkritisi
segala persoalan pelik dengan bungkus humor yang lumayan cerdas, layak mendapat
acungan jempol. Di tangan dan mulutnya, segala persoalan ditelanjangi
habis-habisan, tanpa perlu merasa bersalah ke berbagai pihak yang “terhantam” kritik dan humornya. Memang itulah cara Sujiwo
Tejo. Dengan humornya, masyarakat diajari agar tak mudah meluapkan amarah
apalagi anarki yang lepas kendali dalam
merespon setiap fenomena yang mengusik rasa keadilan. Hasil penelitian Baron (1978), menyimpulkan bahwa humor
dapat menurunkan agresifitas orang yang sedang marah. Bahkan Further et al. (dalam Guilmette, 2008) mengatakan , “humor
mengandung muatan positif yang dapat menurunkan perasaan tegang (tension) dan mengurangi perasaan cemas (anxiety), sehingga membantu orang dalam
masa penyembuhan. Jadi, jangan sepelekan humor!
 |
| Sumber gambar: writeisthenewwrong.blogspot |
Dalam jagat pewayangan, pakeliran Sujiwo dikenal sebagai pentas cerita carangan atau malah cerita sempalan. Buku terbaru Sujiwo Tejo (release beberapa hari lalu), berjudul: LUPA ENDONESA; hakikatnya tak beda dengan pentas wayangnya di atas panggung. Kali ini pentas tidak di panggung pakeliran, namun dituangkan dalam bentuk literasi atau tulisan. Buku LUPA ENDONESA, merupakan kumpulan tulisannya yang terbit setiap hari Minggu di harian Jawa Pos. Publik lebih mengenal sebagai “Wayang Durangpo” ketika masih di Jawa Pos. “Durangpo” sebuah akronim rekaan Sujiwo dari kepanjangan “Nglindur Bareng Ponokawan”. Nglindur (bahasa Jawa) artinya mengigau, jadi “Durangpo” bisa diartikan mengigau bersama Ponokawan. Mengigau artinya berbicara dalam tidur. Orang mengigau yang diomongkan memang sekena-kenanya, tanpa aturan dan batasan. Jadi “Wayang Durangpo” dimaksudkan untuk membicarakan apapun (fenomena yang lagi hangat) dalam gaya humor dan candaan khas para Ponokawan (para abdi kesatria atau raja di pewayangan).
Melalui para Ponokawan, terdiri dari : Semar, Gareng, Petruk, Bagong,
Togog, Mbilung, Cangik dan Limbuk, Sujiwo membedah berbagai permasalahan
kontemporer dalam alur cerita wayang carangan
dan sempalan. Buku LUPA ENDONESA ini terbagi atas 6 tema besar: Cinta Tanah Air, Dasar Manusia, Lupa-Lupa
Ingat, Fulus, Oh, Fulus, Kecanduan Berharap dan Negeri Mimpi, tak hanya menawarkan humor
khas Ponokawan, namun di sana-sini bisa dijumpai
berbagai kerlip butir-butir mutiara
kearifan yang bersumber dari nilai filsafati bahkan agama. Contohnya dalam
personifikasi tokoh Hanoman. Meskipun (Hanoman) berwujud monyet, namun hatinya manusia.
Jadi, “kemanusiaan” seseorang tak tergantung wujudnya, namun tergantung esensi.
Sesuatu yang tak berwujud manusia bisa saja disebut manusia karena punya esensi
“kemanusiaan” seperti Hanoman itu (hal 45).
Dibalik kebengalan celoteh Sujiwo dalam mendalang, Dia tak risih
sesekali menyelipkan pesan moral dan nilai-nilai keagamaan. Dalam dialog
antara Dewi Sariwati dengan Gareng (suaminya), sang Dewi bertutur, “ Ibadah
sembahyang tidak untuk dipamer-pamerkan, yang penting niatnya”. Bahkan, dalil
agama “mendirikan Shalat” dimaknai secara kontekstual oleh Gareng dengan
tuturannya, “ Kalau semua warga sembahyang dengan benar, niscaya tak ada orang
susah di negeri ini, karena semua suka membantu sesamanya” (hal 4). Sebuah
pemaknaan kontekstual “mendirikan Shalat”, yang tak terhenti pada laku ibadahnya tapi ke laku sosial atau kesalehan sosial.
Situasi politik negeri ini pun tak luput dari bidikan celoteh satir
Ponokawannya Sujiwo. Wacana penaikkan harga BBM, yang mencuat beberapa waktu lalu, dengan cerdas
dianalogikan bermuka duanya para politisi senayan (satu muka ke rakyat dengan
menolak wacana penaikkan harga BBM, satu muka lainnya diarahkan untuk menjilat
penguasa dengan menyokong ide penaikkan harga BBM) disamakan dengan muka banyak
yang dimiliki Batara Guru akibat ingin melihat kemolekan Dewi Wilutama yang
selalu beringsut posisinya (hal 156).
Kekonyolan banyolan Sujiwo dalam buku ini ditampakkan antara lain hal
kelupaan Gatotkaca mendaftarkan ke MURI
atas kemampuannya menghancurkan
gunung, berkat ajian Brajamusti dan Brajalamatan yang dimilikinya (hal 30).
Terlepas dari kekurangan yang ada, seperti pemberian judul setiap cerita
dalam bukunya yang terkesan “dipaksakan”, Sujiwo telah berusaha memperkenalkan wayang beserta
ceritanya kepada khalayak luas lewat buku ini.
Meski judul bukunya LUPA ENDONESA
(Indonesia), hakikatnya Sujiwo justru mengajak bangsa Indonesia untuk tidak
melupakan segala persoalan yang ada, melainkan harus menghadapi dan
menyelesaikannya. Pun Sujiwo
mengingatkan bahwa kita memiliki wayang
sebagai warisan adiluhung nenek moyang yang mesti dilestarikan. Bahkan Unesco
sejak 2003 telah mengakui wayang sebagai warisan mahakarya dunia tak ternilai dalam
seni bertutur (Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity),
dan memasukkan wayang dalam Daftar
Representatif Budaya Tak Benda Warisan
Manusia. Jadi, dengan membaca Buku LUPA
ENDONESA ini, justru akan membuat kita tidak apatis dan melupakan segala
permasalahan bangsa. Tak lupa sembari mengingatkan bahwa kita memiliki Wayang yang begitu dahsyat.
Danang Probotanoyo, Centre
for Indonesia Reform Studies, Alumni UGM, Penulis Opini, Esai, Cerpen dan
Timbangan Buku