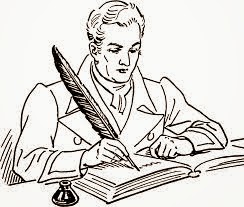Oleh: Danang
Probotanoyo
Judul
Buku : Tart di Bulan Hujan
Pengarang : Bakdi Soemanto
Penerbit : Penerbit Buku Kompas
Cetakan : I, 2014
ISBN : 978-979-709-796-7
Tebal
Buku : viii+198
Ibarat The Three Musketeers, Bakdi Soemanto adalah anggota The Three Musketeers terakhir yang berpulang. Three Musketeers di sini bukanlah tiga ksatria asal Perancis dalam karya Alexandre Dumas yang mendunia itu. Bakdi Soemanto bersama Kuntowijoyo dan Umar Kayam merupakan tiga ilmuwan, budayawan sekaligus sastrawan penting dan utama Indonesia dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Ketiganya berkontribusi besar terhadap perkembangan dan geliat sastra nasional paling tidak selama empat dasa warsa terakhir.
Indonesia, khususnya dunia sastra jelas
kehilangan sekali dengan meninggalnya Prof. Dr. Christoporus Soebakdi Soemanto
(nama lengkap beserta gelar akademis Bakdi Seomanto), pada Sabtu (11/10) di RS
Panti Rapih, Yogyakarta. Entah karena berasal dari institusi yang sama yakni
UGM, Bakdi, Kuntowijoyo serta Kayam memiliki interes yang nyaris seragam dalam
mayoritas karya-karyanya. UGM yang terkenal sebagai “Kampus Rakyat” ada yang
lebih ekstrim menyebutnya sebagai “Kampus Ndeso”,
yakni kampus yang senantiasa berpihak kepada pemberdayaan masyarakat pedesaan
dan marjinal, tak dipungkiri berpengaruh terhadap The Three Musketeers sastrawan tadi. Tema kehidupan masyarakat
marginal dan tradisional sangat mendominasi karya-karya ketiganya. Namun
demikian bukan berarti ketiganya tanpa deferensiasi sama sekali. Kuntowijoyo
kerap menyajikan karya dengan tema mistisisme dan religiositas masyarakat Islam
“tradisonal”. Umar Kayam sering berkutat pada karya-karya yang berlatar
belakang budaya Jawa yang kental. Sedang Bakdi Soemanto, sebagai seorang
penganut Katolik yang taat, memunculkan nilai-nilai dan tradisi kekatolikan
dalam banyak karyanya. Mayoritas karya ketiga Musketeers tersebut dipersatukan dalam aliran sastra realisme. Sastra
yang mengkonfirmasi kenyataan-kenyataan sosial sehari-hari yang hidup di
masyarakat menjadi bahan baku kreasi.
 |
| Resensi Saya di Jawa Pos, Medio: Oktober 2014 |
Pun dalam buku kumpulan cerpen bertajuk
“Tart di Bulan Hujan” ini, Bakdi Soemanto tak lari dari realisme total. Buku
ini berisi 25 judul cerpen Bakdi yang pernah dimuat di beberapa media massa
maupun yang belum pernah dipublikasikan. Berbeda dengan cerpenis umumnya yang
membuat buku antologi berisi karya-karya yang kebanyakan pernah dikabarkan di
media massa. Di buku ini Bakdi justru hanya merilis ulang tujuh karya yang
sudah terpublikasi di media massa. Delapan belas judul sisanya merupakan karya
yang benar-benar “gres” alias belum
pernah dipublikasikan. Ketujuh karya daur ulang itu adalah: Amrok Brokoli,
Muhdom, Kepala, Tart di Bulan Hujan (KOMPAS); Ayam Goreng (The Jakarta Post); Kotak
Suci (Kanisius); Malam Ketujuh Belas (Nova).
Idiom-idiom serta tradisi Katolik menjadi
ornamen penting karya Bakdi dalam
mengangkat tema hidup keseharian masyarakat. Pada “Tart di Bulan Hujan”, betapa
seorang Sum, perempuan sederhana berprofesi pembantu di sebuah home stay, yang hanya bergaji Rp.
250.000 per bulan bercita-cita merayakan Malam Natal dengan membelikan sebuah
tart mahal untuk diberikan ke “bayi Yesus”. Tentangan keras muncul dari Uncok,
suami Sum yang beprofesi sebagai sopir. Di tengah kesempitan hidup yang teramat
dalam, membeli tart berharga ratusan ribu rupiah merupakan sebuah kegilaan,
itulah argumen Uncok menentang cita-cita Sum. Namun berkat campur tangan Tuhan
melalui orang-orang ringan tangan, cita-cita Sum memuliakan “Yesus” tercapai
(hal. 142). Di cerpen “Anjing” menceritakan pengalaman traumatis seorang
Matheus Sardula yang membuatnya absen sekian lama untuk hadir di misa Minggu.
Penyebabnya, Sardula pernah dimarahi Romo karena membuat diorama gua
kanak-kanak Yesus dengan menyertakan miniatur anjing (hal. 9). Nyaris serupa,
pada cerita “Ayam Goreng” dikisahkan bagaimana ibunya Buleneng begitu alergi
untuk hadir di misa malam Natal tersebab adanya tradisi pesta makan ayam goreng
selepas misa di restoran depan gereja tempat tinggalnya. Ibu itu memiliki
pengalaman pahit terkait sang manager restoran ayam tersebut. Akhir cerita,
Buleneng menyadarkan sang ibu agar menyudahi keengganannya hadir di misa malam
Natal dengan mengancamnya akan bunuh diri dengan menggoreng bagian-bagian
tubuhnya sendiri (hal. 21). Buku ini ditutup Bakdi dengan cerita “Selembar Uang
Ribuan”. Meski didalamnya mengangkat kisah rumah tangga Zoziz dan Zabuna,
terselip pula ajakan untuk tak melakukan korupsi. Hal itu tercermin dalam
perilaku Zoziz yang selalu memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan,
bahkan hingga ada ide membeli dua dompet dengan warna berbeda (hal. 189).
Terlepas dari tema dan plot dalam
cerita-cerita di buku ini yang tekesan sederhana dan ringan-ringan saja,
setidaknya banyak makna dan hikmah bisa dipetik. Bakdi Soemanto tentunya sangat
memahami bahwa sebuah karya sastra hendaknya tak lepas dari konsep dulce
dan utile
(menghibur dan berguna) yang ditelurkan Horace itu.
Mencermati karya-karya Bakdi, kita niscaya
menemukan satu keunikan tersendiri, yakni penamaan tokoh dalam cerita yang tak
umum dan susah diingat. Rasanya susah menemukan nama orang Indonesia di dunia
nyata, memakai nama: Muhdom, Kaponyos, Utiyoks, Zwili Zanten, Akar Poteng,
Buleneng, Lumrang, Zozis, Apyun, Wrentel, Wak Zettep dan lain-lain. Diperlukan
keberanian untuk memberi nama tokoh cerita yang serba “ngasal” namun rumit ala
Bakdi tersebut. Bisa jadi kita tak akan menemukan lagi keunikan tersebut,
seiring berpulangnya “Sang Godot”. Selamat jalan Bakdi!
Danang
Probotanoyo, Pegiat Sastra dan Literasi di komunitas Kampung UGM, Alumni UGM