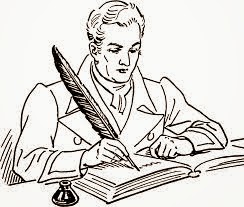Judul
Buku : TIONGHOA DALAM SEJARAH KEMILITERAN
Penerbit : Penerbit Buku Kompas
Cetakan : I, 2014
ISBN : 978-979-709-871-1
Tebal
Buku : xxxviii + 234
Oleh: Danang
Probotanoyo
Berbicara etnis Tionghoa (dulu disebut
“China”), tak akan lari jauh dari topik dagang dan situasi kerusuhan SARA yang
pernah melanda republik. Lainnya hanya mengingatkan orang pada beberapa sosok
pebulu tangkis handal Indonesia. Dalam hal dagang Tionghoa sangatlah dominan. Selain
sudah turun temurun, berbagai politik
diskriminasi yang menimpa mereka sejak zaman VOC hingga Orde Baru,
menempa Tionghoa sebagai pedagang dan pebisnis handal.
Aturan Wijkenstelsel dan Passenstelsel
VOC mencegah interaksi Tionghoa dengan
pribumi. Aturan itu mengakibatkan Tionghoa “terisolasi” di kantong-kantong
pemukiman di perkotaan, dikenal sebagai
Pacinan. VOC memberlakukan aturan itu sebagai buntut pemberontakan Tionghoa
(yang dibantu etnis Jawa) di tahun 1740-1743. Peristiwa “Geger
Pacinan” tersebut dipicu adanya pembantaian Tionghoa di Batavia pada tahun 1740.
Menurut tesis Sejarawan Belanda, Noorduyn, “Geger
Pacinan” menjadi awal serangkaian panjang perang di Jawa. Bahkan dari skalanya,
“Geger Pacinan” dikatakan lebih besar dari Perang Jawa atau
Perang Diponegoro (1825-1830). Entah karena apa, perang tersebut dilupakan
(dihapuskan?) dalam sejarah Nasional. Hingga muncul buku Daradjati berjudul “Geger Pacinan” (2008), yang menguak kembali pemberontakan Tionghoa itu.
Di era Orde Lama, kebijakan diskriminatif
terhadap Tionghoa masih terjadi. Contohnya PP No. 10 tahun 1959, berisi
larangan Tionghoa berdagang eceran di luar
wilayah ibukota provinsi dan kabupaten. Di zaman Orde Baru nasib Tionghoa lebih
buruk lagi. Selain dilarang menyelenggarakan berbagai tradisi seni dan budaya
leluhur, rezim Orba menerbitkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia ( SBKRI), untuk etnis Tionghoa.
 |
| Resensiku di Jawa Pos, Edisi: November 2014 |
Sejarah kelam diskriminasi terhadap Tionghoa
dari masa ke masa berkelindan dengan nasib buruknya sebagai korban pelbagai kerusuhan.
Paling mutakhir adalah kerusuhan Mei 1998, yang mengakibatkan kerugian harta
benda bahkan nyawa etnis Tionghoa. Selalu menjadi korban diskriminasi dan obyek
kerusuhan sejak VOC hingga Orba, menyiratkan ada yang salah dalam memandang
etnis Tionghoa. Banyak yang masih melihat etnis Tionghoa sebagai entitas pendatang.
Meskipun sudah bergenerasi terlahir di Indonesia, tetap saja ada “barier dikotomis”
pribumi dan nonpribumi.
Dengan membaca buku ini niscaya akan mendapatkan
fakta-fakta mencengangkan yang bisa membalikkan sikap dalam memandang Tionghoa.
Buku ini setidaknya mampu menjungkirkan stereotype
bahwa Tionghoa tak lebih dari para pedagang dan pemain badminton. Dalam bukunya
ini, Iwan Santosa mengungkap kiprah etnis Tionghoa yang tak kalah dari pribumi dalam
mendirikan dan mempertahankan eksistensi republik. Ternyata banyak Tionghoa
terlibat langsung dalam perjuangan bersenjata merebut dan mempertahankan
kemerdekaan. Harian Merdeka, koran berpengaruh era 40-an, dalam memperingati
enam bulan kemerdekaan RI, 17 Febuari 1946, menurunkan laporan khusus tentang pertempuran
10 November 1945 dengan judul “Pendoedoek Tionghoa Membantoe Kita”. Dituliskan
bahwa sebagian Tionghoa Surabaya membentuk TKR (Tentara Keamanan Rakyat) “Chungking” yang turut bertempur di garis
depan pertempuran Surabaya. Pertempuran 10 November 1945, yang kini diperingati
sebagai Hari Pahlawan, dengan tokoh
sentralnya “Bung Tomo”, memiliki beberapa nama pejuang Tionghoa di sisi beliau.
Pejuang Tionghoa itu tergabung dalam Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI)
pimpinan Bung Tomo. Tersebut nama Giam
Hian Tjong dan Auwyang Tjok Tek sebagai ahli pyroteknik atau ahli amunisi dan peledak.
(hal.93-95). Dalam pertempuran lain yang tak kalah heroik dengan Pertempuran Surabaya,
yakni “Palagan Ambarawa” ada sosok pejuang terlupakan bernama Kho Sien Hoo.
Sosok Kho Sien ini diungkap ke permukaan
kembali oleh Pramoedya Ananta Toer dalam ulasan buku biografi Ghanda Winata
Bangkit Dan Pantang Menyerah: Kisah Nyata Inspiratif Seorang Prajurit, Pendidik
dan Pebisnis Tionghoa (hal.101).
Setelah perang usai, banyak pejuang
Tionghoa melanjutkan karier kemiliterannya di TNI. Tak sedikit dari mereka hingga
mencecap pangkat perwira. Bahkan penelitian Lie Ay Mei dari Amsterdam, berjudul “Uniform in Diversity”, didapatkan
data bahwa tahun 60-an jumlah perwira TNI bersuku Tionghoa mencapai persentase sama dengan jumlah penduduk Tionghoa di Indonesia, yakni 2-3 persen (hal.206). Sayangnya, karier cemerlang sebagian Tionghoa di TNI
meredup akibat meletusnya G-30 S/PKI. Rezim Orba yang berkuasa pasca peristiwa
itu mencurigai keterlibatan etnis Tionghoa. Kecurigaan keterlibatan Tionghoa
pada G-30 S/PKI sesungguhnya hanya dilihat berdasar “kemesraan” RI-Tiongkok di
era itu. Imbasnya, banyak TNI etnis Tionghoa yang kariernya terhenti atau malah
keluar dari dinas kemiliteran. Selebihnya tetap berkarier di militer dengan
tenaga ekstra agar tetap survive.
Semua kesalahan masa lalu terkait Tionghoa
mulai diperbaiki di era reformasi. Puncaknya adalah penganugerahan gelar
pahlawan nasional dan Bintang Mahaputera Adipradana kepada almarhum Laksamana
Muda (purn) John Lie, pada 9 November 2009, oleh Presiden SBY. Bahkan simbol
heroisme Tionghoa, yang diwakili John Lie, disematkan sebagai nama kapal perang
terbaru TNI AL, yakni KRI John Lie. Buku berjudul “Tionghoa Dalam Sejarah
Kemiliteran” karya Iwan Santosa ini menjadi dokumentasi penting patriotisme
Tionghoa dalam kancah kemiliteran republik yang pada gilirannya bisa membuat
orang memiliki perspektif positif pada Tionghoa.
Danang Probotanoyo,
Centre for Indonesia Reform Studies, Alumni UGM