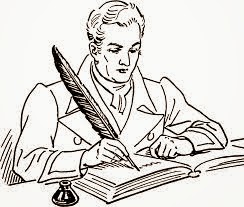Reformasi
Diolok-olok ‘Soeharto’
Oleh:
Danang Probotanoyo
‘Soeharto’ mengejek dari bak-bak truk dan stiker-stiker, “Piye le kabare, penak jamanku ta?” (Jawa). “Bagaimana kabarnya nak, enak di zaman saya
kan?”. Olokan yang sangat tendensius dan klaim sepihak. Propaganda menyesatkan tadi bertebaran di
mana-mana sekarang. Berusaha menggiring psikis Bangsa Indonesia untuk menyesali
bahkan mengutuk penggulingan rezim Soeharto pada Mei 1998.
“Penak jamanku ta?”
merujuk komparasi era Soeharto (Orba) berkuasa dengan era reformasi sekarang. Klaimnya: zaman Soeharto dipersepsikan serba
lebih enak dibanding sekarang. Acuannya pada dua parameter pokok yang cenderung
pragmatis, yakni: sosial ekonomi serta
keamanan dan ketertiban di masyarakat. Betulkah era Soeharto lebih enak?
KKN
‘DNA’ Orba
Era Soeharto, semuanya serba artificial, palsu, ditutupi dan ditekan.
Segala yang nampak ‘baik-baik’ saja,
sesungguhnya kontradiktif dengan realita dan kosmetik belaka. Muaranya demi ‘stabilitas nasional’ (baca: kestabilan
kekuasaan Soeharto).
Terlalu ceroboh klaim semasa
Soeharto kondisi sosial ekonomi serta merta dikatakan lebih bagus. Tak perlu njlimet, argumennya sangat sederhana,
bahwa pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang dicapai Soeharto ternyata
memiliki pondasi yang keropos dan tak langgeng. Segala koar-koar kemajuan,
nyatanya hanya mampu bertahan hingga 1997 saja. Ketika badai krisis moneter
menerjang, orang baru siuman bahwa bangunan ekonomi rezim Soeharto sangat rapuh
dan akhirnya ambruk karena tidak memiliki fundamental ekonomi yang kuat.
Perekonomian era Soeharto disangga tumpukan hutang luar negeri yang dahsyat.
Selaras itu, sumber daya alam Indonesia dikuras asing kolaborator rezim. Terjadi
paradox di era Soeharto: bangsa kaya
raya SDA, tapi hutangnya segunung, rakyatnya pun banyak yang miskin. Biang
keroknya mudah ditebak: bangsa ini dicekik korupsi. Angkanya membuat bergidik.
Rata-rata 40% APBN bocor dikorupsi, itulah yang dikatakan begawan ekonomi
Indonesia, Prof. Soemitro Djojohadikusumo. Trio: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN) menjadi ciri khas era rezim Soeharto. Segala perikehidupan di zaman Soeharto tak luput dari KKN. Dari mengurus
KTP, melamar PNS, masuk ABRI, menjala order proyek, bahkan mencari hutangan ke
bank pun perlu KKN. Ingat, Edy Tanzil yang menggondol triliunan rupiah dari
satu eks bank BUMN kala itu, berkat katebelece
pejabat penting. Banyak pengusaha di era
Soeharto meraksasa dalam sekejap berkat
fasilitas, katebelece dan hubungan
personal dengan pejabat yang kolusif dan nepotis. Ada tren pula, anak atau
saudara pejabat menjadi konglomerat instan yang diendorse kekuasaan orang tua
atau familinya. Mereka rakus memonopoli dan mengkapling negeri ini. Proyek
penunjukan langsung dan berbagai fasilitas kemudahan yang eksklusif dinikmati sanak
saudara dan kroni pejabat. Istilah ‘tata niaga’ marak saat itu, untuk
menyamarkan ‘bisnis broker’ alias bisnis calo keluarga pejabat. Dari bisnis perdagangan
cengkeh hingga jeruk Kalimantan dicaloi anak pejabat. Mereka meraup untung
besar nyaris tanpa modal. Impor ribuan mobil oleh anak pejabat tanpa pajak
menjadi modus culas proyek ‘mobil
nasional’.
Bisnis percaloan keluarga pejabat Orba yang kolusif dan nepotism,
sekarang menurun dan bermetamorfosis
menjadi pengkaplingan bisnis oleh orang parpol. Impor daging sapi ‘jatahnya’
Luthfi Hassan cs. Pengadaan Al Quran oleh Zulkarnaen Djabar dan anaknya, Dendy
Prasetya. Fasilitas olah raga bagiannya M. Nazarudin dan rekan. Dana PPID
teruntuk Wa Ode Nurhayati. Para koruptor tersebut bukan muncul ujug-ujug. Mereka lahir dalam lingkaran
sistem dan budaya korupsi warisan Orba. Mental KKN yang kadung mendarahdaging,
sebagai jejak ‘DNA’ Orba. Penyebabnya karena anasir-anasir Orba pengidap KKN
kronis justru bersimaharaja di setiap infrastruktur politik, lembaga negara dan
birokrasi sekarang ini. Mereka menularkan virus KKN kepada generasi pascaOrba.
 |
| Termuat di Koran Merapi, Medio: Juni 2013 |
Dus, orang Orba bermental korup
masih mendominasi di era reformasi. Labelnya ‘zaman reformasi’, namun
mentalitas dan karakternya masih Orba. Faktanya, reformasi telah dibajak para
Orbais. Itu cukup sebagai penjelas terhadap tuduhan orang bahwa (seolah) era
reformasi KKN-nya lebih marak daripada era Orba. Kuncinya ada di faktor
informasi belaka. Zaman Soeharto nyaris tidak ada keterbukaan informasi publik.
Pers dikontrol ketat, kebebasan bersuara dibungkam. Akibatnya, meski korupsi era
Soeharto merajalela, namun pemberitaannya sangat minim. Hantu breidel bergentayangan
dan sering memakan korban di era Soeharto. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
dikooptasi rezim Orba. Pembedanya: kebebasan pers dan bersuara sekarang sudah
lebih terjamin. Skandal korupsi besar kecil yang melibatkan pejabat atau
kroninya tak akan luput dari santapan publik.
Hal keamanan dan ketertiban masyarakat
dikiranya lebih baik zaman Soeharto. Yang ada rakyat ditekan habis-habisan. Rezim Soeharto kerap
merepresi pihak-pihak yang berseberangan. Kasus penyerbuan kantor PDI, 27 Juli
1996, Trisakti, penculikan aktivis dan penghilangan paksa orang merupakan
catatan buram jelang Soeharto runtuh. Hak milik individu kerap diabaikan. Penggusuran
kepemilikan tanah dan bangunan selalu mengatasnamakan ‘pembangunan’. Ganti rugi
dilakukan semena-mena dan sepihak. Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Jateng bisa
menjadi gambaran ketidakberdayaan petani manakala tanahnya ‘diminta’ negara. Yang
Mbalelo dianggap tidak pro
pembangunan, subversif, apes-apesnya distempeli PKI (Partai Komunis Indonesia).
HAM menjadi tak begitu penting. Peluru kerap dimuntahkan aparat yang menelan
korban rakyat. Tak terhitung, sudah berapa nyawa melayang dalam kasus-kasus
seperti Tanjung Priok, Talang Sari, Sampang dan masih banyak lagi.
Pelestarian
Orba
Klaim ‘penak jamanku’ (enak zaman Soeharto) sangat menyesatkan.
Dihembuskan anasir lama yang masih bercokol. Segala anomali sekarang tak lebih
sebagai warisan Soeharto. Rakyat mudah rusuh, karena selama 32 tahun dikekang
habis-habisan, tak pernah diajari hidup berdemokrasi dan tak ada pembelajaran
keadaban dalam berbeda pendapat. Itu semua buah penyeragaman secara paksa di
era Soeharto.
KKN yang marak saat ini karena mentalitas dan budaya KKN sudah terbangun
kuat sejak era Soeharto. KKN sebagai masterpiece
Orba dilestarikan dan dibiakkan antek-antek Orba yang berkuasa. Perekonomian
yang nampak indah sesaat di era Soeharto menyisakan problem dan hutang hingga
kini. Kekayaan alam semakin habis diobral ke asing sejak dulu.
Tumpukan piring kotor yang ditinggalkan Soeharto tak juga dicuci, karena
politisi dan penguasa binaan Soeharto masih berpesta hingga kini. Jadi, kalau
zaman sekarang dianggap “tak enak”, itu tak lebih sebagai warisan era lalu yang
dilestarikan antek-anteknya.