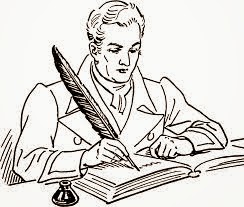Pengarang : Radhar Panca
Dahana
Penerbit : Bentang
Cetakan : I, Maret 2015
ISBN :
978-602-291-047-3
Oleh: Danang
Probotanoyo
Meski di pengantar buku bersampul gambar
karikatur manusia menari berbalut warna dominan gelap yang artistik ini Radhar
Panca Dahana tak menyinggung anniversary
dirinya, namun tetap sah bila ada yang menuduh buku ini penanda lustrum kesepuluh sang penulis. Maret,
di bilangan 26, bertahun “wingit”:
1965, Radhar Panca Dahana mengejawantah manusia sempurna setelah dalam peraman gua garba Ibundanya sembilan bulan. “Manusia
Istana” menjadi buku kumpulan puisinya yang ke-5 dari total 21 buku penerima “Le Prix des pays Francophonique” (award “persemakmuran”
bekas koloni Perancis) itu. Maklum, Radhar adalah sosiolog lulusan Ecole des Hautes
Etudes en Science Sociales, Paris,
Perancis. “Manusia Istana” menjadi adik “Lalu Aku”, buku puisinya yang lahir 2011 silam.
Meski belum setua sastrawan Sapardi Djoko
Damono atau Taufik Ismail, petualangan Radhar di ranah sastra bertunas sejak
belia. Bayangkan, usia 10 tahun telah berhasil menembus keangkeran “screening” redaktur desk cerpen Kompas. “Tamu Tak Diundang” nyatanya terundang sebagai
tamu lembar cerpen Kompas kala itu. Ketika ibunya menancapkan selosin lilin di
kue ulang tahunnya, Ia sudah didapuk menjadi
redaktur tamu di majalah Kawanku. Hanya orang sirik yang mendustakan pengakuan
bahwa Radhar kecil adalah “anak ajaib”. Talenta Radhar tidaklah mekar bersiram
fasilitas apalagi support orang tua, khususnya
sang ayah. Ayahnya, sebagaimana Brotoatmojo – ayah Willybordus Surendra Bhawana
Rendra Brotoatmojo, alias W.S Rendra –
adalah tipikal ayah keras, yang meyakini penyair bukanlah profesi menafkahi. Mungkin
“roh” Plato yang menuding penyair
sebagai warga kelas dua dan lebih inferior dibanding intelektual (baca: filsuf)
pernah merasuki kedua ayah sastrawan kita itu. Entahlah. Minggat dari rumah
menjadi ritual Radhar dan Rendra muda
saat dalam tekanan ayah masing-masing. Bumbu kekerasan fisik ayah terhadap anak
menjadi pembeda nasib Radhar dan Rendra. Betapa Radhar muda sudah katam diterjang
kerasnya tangan sang ayah. Phobia ayunan
tangan sang ayah, membuat Radhar bergidik
dan menyaru menjadi Reza Mortafilini di media massa. Tangan
sang ayah rupanya memiliki radar penjejak yang canggih. Kamuflase Radhar muda
terdeteksi sudah. “Tak ada demokrasi di sini!” begitulah kalimat penutup Radhar
muda dengan bibir berdarah kala oncat
dari rumah untuk kesekian kali. Di titik ini Rendra sedikit lebih
“mujur”.
Ini negeri/ bakal
runtuh dan belah/bila yang lima kau pecah/bila sila silanya berbuah serapah (“Warisan
Akhirmu Soekarno” hal: 43).
Demokrasi yang tereguk sebagai buah
perjuangan dan pengorbanan anak-anak muda di tahun ’98, tidaklah hakiki. Sekadar
demokrasi formalitas, tapi nihil esensi. Demokrasi hanya sebatas kontestasi
pencoblosan gambar di ruang kedap mata. Setelah seremoni dengan imbalan tinta
di jari, orang terpilih justru amnesia
daulat dan amanat rakyat. Sesumbarnya: “kami petugas partai!” Daulat rakyat berganti
daulat partai, daulat ketua umum bahkan daulat makelar politik penyokong kapital.
 |
| Resensi Saya di KORAN TEMPO, Edisi: Juni'15 |
Pemilihan besar
ini sekadar opera/dengan aktor aktor yang hina/ sutradara durjana dan musik
yang genit membuat lupa/ /juragan juragan picik tak sabar menunggangi sejarahmu/
menguliti habis kuasamu/ memeras kering harta rakyatmu/ inikah arti pesta itu?/
tangis berjuta di kakimu?/ inikah hasil kemenangan itu?/ Kontrak kontrak
politik, bisnis, garansi modal kekuasaanmu? (“Air Mata Umara 2”, hal: 71).
Di buku ini Radhar menyatroni nyaris semua isu politik yang
bergentayangan di negeri para politisi ini. Bahkan yang teraktual Ia lumat
tandas menjadi residual kata-kata artistiknya.
Cerita retorika
dimainkan/ kebijakan diputuskan/ perdebatan digulirkan/ ramai benar rumah negara
kita/ seolah benar negeri ini ditata/ tapi di ujung telepon/ atau sudut ruang
pemerintahan
tekanan tawar
menawar dan ancaman/ mendahului semua cerita/ melampaui segala prakira. (“Sejilid Komik
Kritik Politik”, hal: 131). Puisi tadi boleh jadi pengisahan sengkarut
pencalonan durjana bakal kepala bhayangkara. Bisa pula tidak. Terserah pembaca
menafsirkannya. Toh, Paul Ricoeur
sudah berwasiat bahwa teks bersifat polisemis, tergantung kita memaknainya.
Buku puisi penanda Radhar Panca Dahana setengah
abad ini sungguh paripurna. Sayangnya, di antara deretan tokoh yang
“mengendorse” buku ini terselip satu nama yang mengganggu: seorang politisi yang sedang dibui karena
korupsi! Sayang!
Danang
Probotanoyo, Aktifis Literasi dan Sastra “Komunitas Kampung UGM”