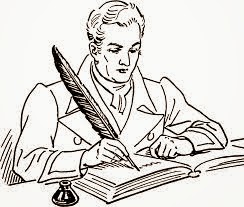Oleh :Danang Probotanoyo
Statusnya tak lagi sebagai staf rendahan di kantor. Kata orang, dia
sekarang menduduki jabatan struktural di instansinya. Gaji besar dan aneka
tunjangan membuat perlente Brutus sekeluarga. Brutus telah menjelma jadi kaum
borjuis baru di kampungnya.
 |
Cerpenku Termuat di Malang Post, Februari 2014
|
Berbilang tahun Brutus tidak
mau lagi menghadiri sekedar undangan kenduren di rumah warga yang berhajad. Merasa
disepelekan, warga pun tak ada lagi yang mengundang Brutus kenduren. Pertemuan warga sebulan sekali pun telah ia tinggalkan
tiga tahun lalu. Menghindari komplain, ia membayar segala uang iuran secara
lebih dari seharusnya. Itulah strategi yang diterapkannya. Mottonya: semua bisa
dibeli dengan uang. Nyonya Brutus pun tak lagi menampakkan batang hidungnya di arisan
ibu-ibu PKK di
kampungnya. “Nggak level, mosok cuma
ngurusin duit cebanan,” Nyonya Brutus ketus. Maklum,
sekarang dia punya kelompok arisan sendiri yang beranggotakan ibu-ibu istri pejabat
dan sosialita lainnya. Sekali kocokan bisa untuk shooping
ke Singapura.
Pagi itu Brutus tidak ngantor. Tuan dan Nyonya Brutus akan ke bandara untuk menjemput neneknya Bagus – Ibunda Brutus.
Rencananya, si nenek akan menetap permanen di rumah Brutus. Maklum, sebagaimana Brutus, si nenek pun hanya
memiliki satu keturunan, ya Brutus itu. Sekarang sang nenek sudah
mulai sakit-sakitan. Brutus memutuskan untuk merawat sang nenek di rumahnya.
Meski sudah ringkih karena dimakan usia dan berbagai penyakit, sesekali jika
rumah sedang sepi, sang nenek kerap pergi jalan-jalan di sekitar lingkungan rumah
Brutus. Sesekali ia mampir ke warung
kelontong milik Bu Surti untuk membeli Rheumason. Dari Bu Surtilah sang nenek banyak
tahu tabiat keluarga anaknya yang menjauh dari pergaulan lingkungan.
Sang nenek masygul mengetahui itu. Namun tak sampai hati untuk
menegur anak semata wayangnya. Dicarinya cara yang tepat untuk berbicara soal
tersebut agar tak mengecewakan Brutus.
“Tadi habis Maghrib
aku lihat bapak-bapak pada berjalan bareng sambil bawa besekan,
pada kenduren,
ya, ‘Tus? tanya nenek suatu ketika.
“Iya, Bu, mereka
memang suka mengadakan kenduren. Bagi
tetangga yang lainnya, itu
sangat membantu, adanya
besekan berarti saat itu mereka tidak
perlu repot-repot ngliwet.
Kalau di tempat
kita kan makanan sudah melimpah, enak-enak lagi, jauh dibanding
besekan
itu,” Brutus ketus.
“Betul, Bu. Lagian di rumah
ini tak ada yang suka makan nasi keras, nanti bisa usus
buntu, Bu,” timpal Nyonya
Brutus tak kalah pedasnya.
“Ya, sekali-kali
berangkat kan nggak apa-apa, buat pergaulan, Tus, apalagi bila itu
selamatan untuk orang meninggal, kan
keluarga yang ditinggalkan sedikit terhibur tidak
merasa sendirian,” nasehat
Nenek.
“Nggak ada waktu
lagi ngurusin hal-hal begitu, Bu.”
Nenek terdiam,
satu poin tentang Brutus klop dengan omongan Bu Surti di warungnya tempo hari.
Tiga hari
berlalu, ketika Brutus dan nyonya mengantar nenek periksa ke dokter.
“Hampir setiap malam aku melihat Tinah, pembantu kalian, memasukkan uang
dalam
plastik dan meletakkannya di dekat kotak surat di pagar, buat apa itu,
Tus?” tanya nenek.
“O, itu uang sokongan buat yang piket ronda. Kata Pak Nardi
si tukang sampah, setiap
warga kena tarikan lima ratus rupiah setiap malamnya. Aku setiap malam malah pasang
lima ribu, kok, Bu, biar nggak dikejar-kejar buat ronda. Maklum, aku
sangat sibuk dan
banyak kerjaan, jadi ya aku ganti jatah rondaku dengan uang,” jawab Brutus.
“Memang bisa begitu? Apa nggak sebaiknya sekali-kali berangkat?! Buat
pergaulan juga
Kan.”
“Saya kan orang sibuk, Bu, nggak seperti mereka. Uang sokongan saya sudah
jauh
melampaui dari yang seharusnya, kok.”
“Mas Brutus nggak tahan angin malam, Bu, nanti kalau masuk angin, kita juga
yang
repot,” sela Nyonya Brutus.
Nenek terdiam.
Merenung sebentar. Setelah menata batinnya akhirnya sang nenek angkat
bicara untuk menasehati anak dan menantunya. Intinya sang nenek berwasiat
bahwa sekaya apapun dan sesukses apapun,
manusia tetaplah mahluk sosial yang saling tergantung satu sama lain. Namun mental, lagi-lagi alasan sibuk selalu dijadikan dalih. Brutus
pun mengatakan bahwa pergaulannya di luar kampung cukup banyak. Nenek tetap
mencoba menasehati. Tetap tak mempan. Nenek frustrasi. Segala
nasehatnya bagai angin lalu bagi seorang Brutus.
Satu setengah tahun setelah tinggal di
rumah Brutus, sang nenek pun wafat. Meninggalkan sebuah wasiat agar
jenazahnya dimakamkan di pemakaman kampung dimana Brutus tinggal. Sebenarnya
Brutus tidak setuju. Namun apa mau dikata, wasiat terbaca setelah ibunya wafat. Brutus
mesti menjalankan wasiat tersebut. Prosesi pemakaman berjalan tersendat
karena untuk menggali makam buat ibunya, Brutus harus mencari orang sewaan terlebih dulu.
Tak ada seorang warga pun yang bersedia menggalikan makam. Pun untuk mengangkat
keranda jenazah ibunya, Brutus terpaksa mengerahkan anak buah dikantornya.
Kepedihan keluarga Brutus semakin menjadi
di hari ketiga kematian ibunya. Brutus mengalami pergulatan batin yang luar
biasa antara rasa duka dan penyesalan mendalam. Pikirannya campur aduk,
dipandanginya tumpukan kardus selamatan ibunya yang masih tertumpuk
dengan rapi di ruang tamunya. Padahal kardus itu bukan kardus sembarangan. Di
pesan dari sebuah catering ternama. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul
sepuluh malam. Tetangga yang diundang
untuk selamatan tiga hari ibunya berpulang, tak satu pun yang mau datang. Celakanya,
semua saudara dan handai taulan sudah berpamitan pada hari kematian. Maklum,
semuanya orang sukses dan orang sibuk di Jakarta dan Surabaya. Tak ada kumandang
Yasin apalagi do’a buat ibunya. Tumpukan
kardus kendurian menjadi saksi bisu sebuah penghukuman. Namun terlambat, keluarga Drs. Brutus sudah
terlanjur diboikot warga. Tumpukan uang dan gemerlap jabatan tidak lagi
bermakna dalam kondisinya saat itu. Mungkin
itulah cara Ibunda Brutus untuk menyadarkan anak dan menantunya.
Yogyakarta,
Januari 2014