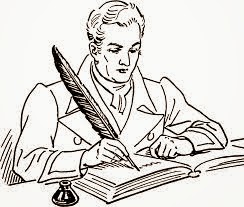Oleh: Danang
Probotanoyo
 |
| Cerpen Saya di Minggu Pagi, Medio: Juli 2015 |
Ramadan 1436 H. kali ini bagi Muzdalifah
hanya mengulang Ramadan tahun-tahun yang lalu. Makan sahur sendiri tanpa
ditemani Fajar, suaminya. Meski Muzdalifah ikhlas menjalani, namun hatinya gundah
melihat kekerasan hati Fajar yang sudah tiga tahun tak lagi bersantap sahur di
rumah bersamanya. Di keramaian suasana Ramadan di kampung-kampung seantero
negeri, kesunyian justru memagut batin Muzdalifah. Sedih, sesal, pasrah dan
ikhlas melebur jadi satu.
“Kau tahu, di Ramadan itu kita kehilangan
segalanya! Milik kita yang paling berharga
kini tiada lagi. Kita kehilangan harapan, Bu!” kalimat kegusaran Fajar yang
selalu diulang-ulang.
Masih
terngiang-ngiang Ramadan tiga tahun lalu sehabis bersantap sahur, Rudy
berpamitan kepada ayah dan ibunya untuk menunaikan shalat subuh di Masjid
Agung, kotanya.
“Kenapa mesti di Masjid Agung, Rud?
Masjid An-Nur kampung kita kan cukup,” ujar Fajar kepada anaknya.
“Sekarang kan hari Minggu. Sekali-kali
Rudy ingin merasakan suasana Ramadan di waktu subuh di Masjid Agung,” Rudy
merajuk ke ayahnya.
“Sesekali nggak apa-apa, Pak. Rudy kan sudah
besar, sudah kelas dua SMP. Bisa menjaga dirinya sendiri,” Muzdalifah mencoba
meyakinkan Fajar.
“Iya, maksudku di masjid kampung kita kan
sudah cukup, nggak perlu jauh-jauh ke Masjid Agung di alun-alun itu,” Fajar
mencoba berargumen.
Muzdalifah
tersenyum melihat gelagat Fajar mulai luluh pertanda mengizinkan.
 |
| Cerpen Saya di Minggu Pagi, Medio: Juli 2015 |
“Bersama siapa Kamu akan ke Masjid Agung,
Rud?” tanya Muzdalifah.
“Kami bertiga, Bu, bersama Agus dan
Farid,” jawab Rudy sumringah.
“Hati-hati di jalan! Pulangnya jangan
terlalu siang ya!” pesan Muzdalifah.
Sambil
menghampiri dan mencium tangan bapaknya, Rudy pun pamit.
“Ingat pesan ibumu, Le,” pungkas Fajar datar.
“Iya, Pak, jangan khawatir,” Rudy pun melangkahkan
kaki melewati ambang pintu depan rumahnya. Di teras sudah menunggu Agus dan Farid, teman
sekampungnya.
“Gimana, Rud, bapakmu membolehkan Kamu
pergi, kan?” tanya Agus was-was.
“Iya, Rud, segede ini mestinya kamu tak
dipingit lagi oleh bapakmu itu. Anak cowok, gitu lhoh,” ledek Farid.
“Kalian lihat sendiri, aku tadi sudah cium
tangan bapakku. Artinya ya diizinkan. Ayo, keburu adzan subuh. Kita masih harus
jalan kaki dua puluh menit untuk sampai di alun-alun,” tukas Rudy. Tiga sekawan
remaja tanggung itupun bergegas berangkat ke Masjid Agung.
Fajar
tak jua beranjak dari meja makan menanti datangnya imsak sembari menghabiskan
rokok di tangannya yang tinggal separuh. Sambil memunguti piring dan gelas
kotor sisa makan sahur bertiga, Muzdalifah berkata kepada suaminya,
“Rudy sekarang sudah besar, ya, Pak. Ada
baiknya mulai kita beri kepercayaan. Jangan kita kekang-kekang lagi.”
“Aku tak mengekangnya, Bu. Aku hanya
ingin memastikan Rudy baik-baik saja. Aku tak ingin Rudy hilang dari pengawasan
kita,” kilah Fajar sambil menyeruput teh panasnya.
“Iya, Pak, aku sadar, Bapak sangat sayang
pada Rudy. Begitupun aku terhadapnya. Tapi sekarang Rudy sudah bukan anak kecil
lagi. Sewajarnya bila kita memberi kebebasan layaknya teman-teman sebayanya.
Takutnya Rudy nanti menjadi anak minder, lho, Pak,” Muzdalifah mengingatkan
suaminya.
“Kamu harus ingat, Bu, betapa kita mesti
menunggu sangat lama kehadiran Rudy di tengah-tengah kita. Sepuluh tahun rumah
tangga kita sepi tanpa kehadiran seorang anak. Berbagai upaya telah kita
tempuh, tapi anak yang kita dambakan tak jua hadir. Baru di tahun kesebelas
perkawinan kita, dokter Heru memberi kabar baik tentang kehamilanmu itu. Kalau
akhirnya Rudy menjadi satu-satunya keturunan kita, sudah sangat wajar bila aku
selalu menjaganya, karena aku sangat sayang padanya melebihi apapun juga.”
Meski
dalam hatinya ada sedikit ketidaksetujuan pada pandangan suaminya, namun Muzdalifah
tak ingin berdebat lebih lama lagi. Apalagi waktu imsak tinggal lima menit.
“Hampir imsak, Pak, rokok dan tehnya
segera dihabiskan,” ingat Muzdalifah.
***
Seusai
salat subuh dan mendengarkan ceramah seorang kyai besar di kota itu, Rudy dan
kawan-kawannya beranjak dari halaman Masjid Agung yang persis bersebelahan
dengan alun-alun kota. Suasana selepas subuh itu sangat ramai di alun-alun. Pemandangan
yang biasa dijumpai selepas subuh di pusat kota. Apalagi hari itu bertepatan
dengan hari minggu. Banyak orang – yang sebagian besar anak muda – berjalan-jalan
mengitari alun-alun atau sekadar bergerombol duduk-duduk di trotoar. Di
sana-sini terlihat beberapa remaja menyalakan petasan penambah kemeriahan
suasana. Ratusan hingga ribuan remaja, dewasa hingga orang tua lainnya
nampaknya tengah menunggu sesuatu.
Rudy
ingin bergegas pulang, teringat pesan ibunya. Tapi Agus dan Farid memiliki
rencana lain.
“Ayolah, Rud, jangan buru-buru pulang.
Kapan lagi Kamu memiliki kebebasan seperti pagi ini?” bujuk Agus kepada Rudy.
“Iya, Rud, mumpung kita sekarang ada di
alun-alun. Sekali-kali nonton hiburan gratis yang menegangkan ini. Kapan lagi
bisa begini kalau tidak pas Ramadan?” timpal Farid.
Pada
mulanya Rudy enggan menuruti kemauan kedua temannya itu. Namun kalau harus
pulang sendirian tanpa keduanya, Rudy juga tak mau. Terpaksalah Rudy menunda
kepulangannya dan hanyut dengan ribuan orang di alun-alun itu bersama Agus dan
Farid.
***
Hari
ini hari Minggu, hari ke tujuh belas Muzdalifah berpuasa. Sang Surya perlahan menuju
peraduannya di cakrawala barat. Setelah menanak nasi dan membuat teh bakal buka
puasa, Muzdalifah bergegas ke pemakaman desa. Kakinya melangkah menuju sudut
barat makam di bawah pohon kamboja besar. Benar, disana sesosok lelaki yang
mulai menua tengah duduk tertidur menyandarkan kepala pada sebuah pusara. Ia
menghampiri lelaki itu, ditepuk-tepuk pundaknya dengan pelan. Setelah
terbangun, Muzdalifah membantunya
bangkit berdiri dan memapahnya.
Fajar
menggerutu, “Kaulah yang menyebabkan kita kehilangan anak satu-satunya, Bu!
Seandainya tidak Kau cegah saat aku melarangnya ke Masjid Agung itu, tentu Rudy
tidak menonton balapan liar di alun-alun hingga menyebabkan ajalnya tertabrak motor
salah satu diantara mereka.”
Muzdalifah
membisu, diusapnya lelehan air mata sambil memapah pulang suaminya. Sayup-sayup berkumandang azan maghrib.
Danang
Probotanoyo
Pegiat Literasi
& Sastra di “Kampung UGM”