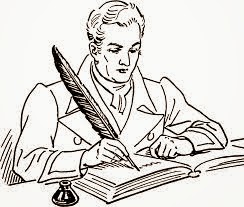|
| Termuat di KORAN MERAPI, Medio: Juli 2013 |
Jejaring
Sosial di Bulan Ramadhan
Oleh
: Danang Probotanoyo
Meski tahun 2013 ini, umat Muslim di tanah
air memulai puasa Ramadhan 1434 H tidak bersamaan – ada yang mulai tanggal 9
Juli dan 10 Juli – namun hal itu tidak perlu dipermasalahkan. Semua pasti
memiliki dasar masing-masing dalam menentukan datangnya bulan Ramadhan. Semuanya
tentu ingin melaksanakan ibadah puasa Ramadhan yang telah menjadi kewajibannya,
sebagaimana difirmankan dalam Al Qur’an (Al Baqarah: 183): “Wahai orang-orang
yang beriman diwajibkan atas kamu sekalian puasa, sebagaimana diwajibkan atas
orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertaqwa.”
Yang perlu menjadi pemikiran bersama adalah kualitas dari ibadah puasa itu
sendiri. Karena tak banyak dari umat Islam yang mau melakukan introspeksi,
apakah puasa yang dilakukannya sudah benar atau belum. Banyak orang merasa
bahwa ibadah puasa Ramadhan yang dikerjakannya sudah memenuhi syarat dan rukun puasa.
Mereka cukup puas bahkan sudah merasa benar dalam berpuasa. Padahal puasa tidak
cukup hanya dengan menghindari beberapa hal yang membatalkan puasa, seperti:
makan dan minum, bersenggama, memasukkan makanan ke dalam perut, keluarnya air
mani dengan sengaja, keluarnya darah haid dan nifas, sengaja muntah dan murtad.
Nyaris banyak yang melupakan nilai dan kualitas ibadah puasanya. Padahal nilai
kualitas dari ibadah puasa juga sangat esensial, sebagaimana hadist sahih Rasulullah SAW, yang
diriwayatkan HR Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, yang menyatakan bahwa
banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak menghasilkan apa pun dari puasanya,
selain lapar dan haus. Hadis ini mengisyaratkan secara tegas bahwa hakikat
shaum (puasa), bukan hanya menahan lapar, dahaga dan hal-hal lain yang
membatalkan, akan tetapi, puasa adalah menahan diri dari ucapan dan perbuatan
kotor yang merusak dan tidak bermanfaat. Yang tidak kalah penting adalah
kemampuan untuk mengendalikan diri terhadap cemoohan, makian dan hinaan dari
orang lain. Secara umum orang yang berpuasa mampu menahan diri dari makan dan
minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun banyak diantaranya
yang tidak mampu mengendalikan diri dari
hal-hal yang dapat mereduksi bahkan merusak pahala puasa.
Salah satu yang bisa mengurangi nilai
ibadah puasa seseorang adalah melakukan ghibah, yakni memperbincangkan
keburukan dan aib orang tanpa ada niat untuk memperbaikinya. Ghibah inilah yang
seringkali dilakukan tanpa sadar. Nyaris dimana pun dan kapan pun orang
senantiasa berghibah. Apalagi di era kemajuan teknologi informasi, ghibah
begitu mudahnya terjadi. Di program acara televisi bertebaran tindakan
berghibah. Dari acara berita, talk show,
apalagi acara-acara hiburan semacam infotainment, yang kerap mengulas sisi-sisi
buruk orang. Semakin ‘miring’ isi reportase, semakin membuat orang penasaran
untuk menyaksikannya. Substansi, fakta, obyektifitas dan etika terkadang
dikorbankan. Yang dikejar adalah rating. Semakin banyak ditonton orang, semakin
tinggi ratingnya. Rating akan menjadi acuan para pemasang iklan. Ujung-ujungnya
adalah profit. Masalah halal haram jarang dipikirkan. Padahal, sebagaimana
sabda Rasulullah (diriwayatkan Nu’man bin Basyir radhiyallahu ‘anhu) “Sesungguhnya
perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada
perkara-perkara yang samar (syubhat), yang tidak diketahui oleh banyak
manusia,...”
Ghibah juga terjadi di media selain
televisi, misalnya di surat kabar, majalah dan radio. Namun semua media
‘konvensional’ tadi belum ada apa-apanya dalam ‘memfasilitasi’ terjadinya
ghibah bila dibandingkan media termuktakhir yakni internet. Sifat internet yang
fleksibel, berjangkauan nyaris tak terbatas, bisa digunakan serta diakses siapa
saja, menjadikan internet bak pisau bermata dua. Satu sisi bisa menyebarkan
hal-hal yang bersifat positif, mencerahkan dan membangun. Sisi yang lainnya
bisa bersifat destruktif, termasuk untuk berghibah. Media jejaring sosial,
macam facebook dan twitter, sebagai derivate
product internet, sangat mudah
digunakan siapa saja untuk membicarakan keburukan dan aib seseorang. Lebih-lebih
bila informasi yang disampaikan hal seseorang adalah informasi palsu (hoax), ujung-ujungnya terjadi cyber bullying atau kekerasan di dunia
maya. Bila itu terjadi, maka dampaknya sangat luar biasa bagi si korban, karena
dalam waktu sekejab, unggahan atau status yang bersifat ghibah bisa menyebar ke
seantero dunia.
Untuk itu di bulan suci ini, seyogianya
kita bisa menggunakan internet dan jejaring sosial untuk hal-hal yang positif
dan bernilai ibadah. Bisa dimulai dari mengunggah status yang bersifat
keagamaan, misalnya up load ayat Al
Quran, Hadist Nabi hingga kisah-kisah sufi. Boleh juga mengunggah hal-hal yang
ringan terkait bulan Ramadhan, misalnya sharing
resep pembuatan kolak, aneka makanan untuk berbuka atau reportase kegiatan
masjid di lingkungan masing-masing dalam mengisi bulan Ramadhan. Bila teknologi
informasi yang ada dimanfaatkan untuk lebih mensyiarkan dan menambah ghirah
ibadah puasa, Insya Allah puasa akan memiliki nilai ibadah yang tinggi dan
bermanfaat bagi sesama. Dengan demikian kita tak hanya mendapat lapar dan
dahaga dalam menjalani ibadah puasa Ramadhan.
Ramadhan 1434 H (2013)